Pernah dengar ucapan kayak gini?
“Ah, orang Sunda mah santai, nggak ambisius. Malas juga.”
Ucapan itu terdengar seperti bercanda, tapi ternyata mengandung stereotip yang cukup serius. Label “orang Sunda pemalas” sudah beredar sejak lama, bahkan bisa muncul dalam percakapan sehari-hari atau media. Tapi, pernahkah kita tanya: dari mana sebenarnya stigma ini datang?
Apakah Ini Berdasar Fakta Sejarah?
Kalau kita lihat dari sejarah, tidak ada catatan masa klasik yang menyebut orang Sunda sebagai pemalas. Kerajaan-kerajaan besar di wilayah Sunda seperti Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran menunjukkan kemajuan dalam hal pemerintahan, budaya, dan kehidupan masyarakatnya.
Bahkan, naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Prasasti Tugu menunjukkan bagaimana orang Sunda terlibat aktif dalam sistem irigasi, perdagangan, hingga spiritualitas. Artinya, aktivitas dan produktivitas masyarakat Sunda tercatat dengan jelas, jauh dari kesan pasif apalagi malas.
Peran Kolonial Belanda dalam Membentuk Stereotip
Nah, di sinilah peran kolonialisme mulai muncul. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial membuat klasifikasi etnis untuk keperluan pengelolaan tenaga kerja dan pengendalian sosial. Mereka menciptakan “profil” tiap suku:
- Orang Jawa: patuh dan pekerja keras
- Orang Batak: keras tapi jujur
- Orang Sunda: ramah, lembut, tapi... katanya kurang rajin
Profil ini bukan hasil riset objektif, melainkan narasi yang dibentuk sepihak oleh penguasa kolonial, untuk menyesuaikan kebutuhan mereka sendiri. Karena masyarakat Sunda tidak banyak direkrut dalam proyek kerja paksa atau tanam paksa, maka muncullah cap “tidak cocok jadi buruh” yang akhirnya dianggap malas.
Lingkungan Alam & Pola Hidup Jadi Faktor?
Kalau kita lihat lebih dekat, alam Tatar Sunda memang cenderung subur dan sejuk. Tanahnya mendukung pertanian, air melimpah, dan suhu nyaman. Ini memengaruhi cara hidup masyarakat:
- Lebih agraris dan dekat dengan alam
- Gaya hidup cenderung tenang dan tidak terburu-buru
- Mengedepankan keseimbangan daripada ambisi besar-besaran
Tapi pola hidup seperti ini bukan berarti malas. Justru bisa dibaca sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan dan filosofi hidup yang lebih selaras.
Stereotip yang Terus Diulang di Budaya Populer
Sayangnya, label ini tidak berhenti di masa kolonial. Banyak media, sinetron, hingga candaan di media sosial masih mengulang narasi ini tanpa sadar. Bahkan, kadang digunakan untuk membandingkan antar suku yang justru memperkuat prasangka.
Padahal, semua orang, baik Sunda, Jawa, Batak, Minang, dan lainnya, punya keunggulan dan dinamika sendiri. Menempelkan label malas pada satu suku adalah bentuk reduksi yang tidak adil.
Waktunya Bertanya Ulang: Dari Mana Asal Tuduhan Ini?
Daripada ikut-ikutan bilang “orang Sunda pemalas,” mungkin kita perlu bertanya ulang:
- Apakah label ini benar-benar lahir dari kenyataan?
- Atau justru dari siapa yang menulis sejarah?
- Siapa yang diuntungkan dari narasi ini?
Karena dalam banyak kasus, yang menulis sejarah adalah mereka yang berkuasa, dan kadang apa yang ditulis bukan kebenaran, tapi alat kendali.
Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Mulai dari hal kecil: jangan langsung percaya dengan stereotip. Kalau kita bisa membaca sejarah lebih utuh dan kritis, maka label seperti ini tidak akan bertahan lama. Jadikan literasi sebagai alat untuk membongkar mitos yang merugikan.









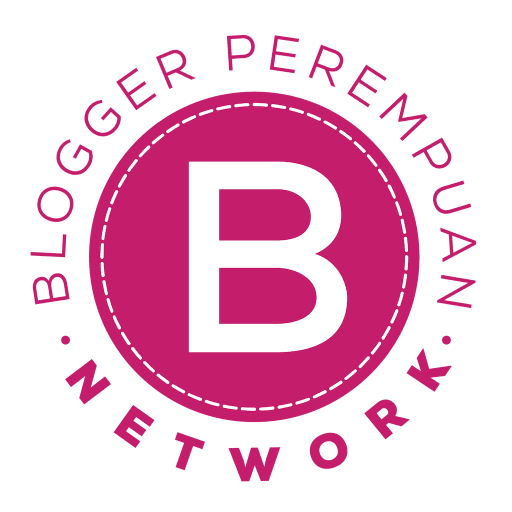


0 Komentar